Sabtu malam itu, 24 Mei 2025, tepat di malam penutupan Festival Maumerelogia 5, bagiku- Maumere bukan sekadar salah satu titik geografis di sekujur tubuh peta Nusa Tenggara Timur, kota ini menjadi paranada, tempat digambarkannya not-not balok dengan irama dan vibrasi yang hidup.
Meskipun menjadi higlight, konser musik dengan tajuk Melodi Kota menjelma ruang kebersamaan dan bukan sekadar penutup agenda kebudayaan. Setelah Silampukau pamit dari panggung, aku memilih berdiri di garda terdepan. Bertemu wajah dengan pagar pembatas dan terang spotlight yang membelah langit malam dan membakar stage bersama semangat penonton. Beberapa pemuda dengan antusias menyeruduk keramaian, memeluk pagar besi pembatas di sebelahku dan meneriakkan sebuah nama: PostMan- salah satu band penampil malam itu.
Orang-orang tidak bisa diam. Mereka seperti dihipnotis oleh hentakan lagu-lagu yang bergenre reggeae- aliran musik yang lahir dari suara-suara tertindas, dari pergulatan sejarah, dari kebutuhan untuk bertahan, melawan, dan merayakan hidup.
Mungkin mereka pun sedang berjuang, sedang melawan, atau sedang merayakan sehingga lirik-lirik lagu yang dibawakan PostMan menjelma representasi kehidupan harian mereka. Tapi bagiku, ada sebuah lagu yang liriknya indah sekaligus menggelisahkan.
Bunyinya begini,“Deeper The Roots, Stronger The Tree“
Lirik itu lebih dari sekadar perlawanan. Ia adalah melodi perenungan. Tentang kota, tanah, akar. Keriuhan pementasan itu justru menjadi ruang diskusiku dengan diri sendiri, dengan tanah tempatku berdiri, dengan panggung nan megah: Apa yang deeper the roots dan stronger the tree di kota kita ini?
Spotlight yang membakar panggung malam itu mengingatkanku pada spotlight lain: Sorot yang kini mulai diarahkan pada Maumere sebagai kota yang tumbuh. Tapi pertumbuhan itu seperti bayangan,ia tidak selalu jelas bentuknya.
Dengan mata perempuan muda sepertiku, yang lahir dan besar di kota ini, aku sedang melihat Maumere bukan sebagai kota yang ingin menyamai Jakarta atau lainnya, ia berdiri sebagai “entitas” sendiri. Tapi justru itu yang membuatnya menjadi tempat di mana hal-hal paling jujur terasa.
Menjadi orang muda di Maumere hari ini juga berarti tumbuh dalam dualitas. Kita hidup antara bunyi gong dan nada dari perangkat gawai. Kita berada di antara adat dan alogaritma media sosial. Kita bisa duduk mengelilingi tungku api sambil mengedit konten TikTok. Kita bisa belanja di pasar dengan uang pas-pasan, lalu pulang dan menulis puisi tentang keberlanjutan.
Kita merayakan misa pagi, lalu diskusi tentang aktivisme dan ekofeminisme malam harinya. Kita generasi yang lahir di tanah yang belum selesai disebut kota, tapi juga bukan lagi murni kampung. Maumere hari ini belum sepenuhnya kota, tapi ia juga bukan kampung yang naif. Ia adalah ruang transisi. Dan kita generasi muda, adalah penghuninya. Kita yang menonton panggung sambil memotret, menangis diam-diam, dan menyimpan lirik reggae sebagai mantera perlawanan batin.
Malam itu, di tengah dentuman bass dan sorakan penonton, aku sadar satu hal: menjadi bagian dari Maumere adalah menjadi bagian dari proses. Proses mencari akar yang lebih dalam dari akar, dan kekuatan yang lebih kokoh dari pohon.
Menjawabi pertanyaan ini, aku teringat pada nenekku yang menyimpan doa-doa dalam bahasa asli kita yang sudah nyaris hilang. Bahasa yang mungkin tidak senantiasa dipakai dalam keseharian tapi dapat dipahami bersama maknanya. Aku memikirkan cara orang-orang menyebut Maumere bukan sebagai tempat, tapi sebagai rumah.
Dan aku sadar, sesuatu yang depeer the roots atau yang lebih dalam dari akar adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi selalu terasa, namanya adalah ingatan kolektif atau memakai istilah sosiolog Maurice Halbwachs, itu berarti memori bersama yang tak pernah ditulis tapi diwariskan, melalui moke, pangan lokal, motif tenun ikat, senyuman, bahkan lagu-lagu lisan.
Maumere menyimpan sesuatu yang tidak bisa direkam dengan kamera drone, ia hidup dalam cara kita memanggil sesama “saudara”, meski berbeda agama. Dalam cara kita menyebut arah bukan “utara-selatan” tapi “atas–bawah”, mengikuti letak gunung dan laut.
Bagiku, inilah fondasi pertama kota yang belum sepenuhnya kota, tapi sudah tidak bisa disebut kampung. Kota yang tidak dibangun hanya dengan beton dan kabel listrik, tapi dengan jalinan-jalinan sakral seperti bahasa Ibu, lagu, ingatan, dan kebersamaan.
Belum selesai di sini, ada pertanyaan lanjutan lagi yang harus dijawab: apa yang stronger the tree, atau apa yang lebih kuat dari pohon?
Jawabannya datang dalam bentuk yang paling manusiawi: resilience, daya tahan, daya lenting, ketangguhan.
Daya lenting masyarakat bukan sekadar bertahan, tapi kemampuan untuk tetap menjadi manusia yang berdaya saat hidup menguji habis-habisan.
Meminjam istilah A’an Mansyur tentang posisi masa lalu, kita dipanggil menengok ke depan-ke sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya bahwa kota ini pernah luluh lantak oleh gempa, pernah dipinggirkan dalam banyak hal. Tapi kita tetap menyanyi dengan ciri khas kita sendiri, menulis lagu dengan kekayaan bahasa sendiri. Kita tetap menari dan menciptakan ragam-ragam tarian meskipun ditambah istilah “kreatif” di belakangnya, mungkin dengan maksud agar bisa fit in dengan zaman.
Kita beradaptasi dengan teknologi tapi diam-diam menolak diseragamkan. Kita tetap datang ke festival-festival kecil dengan kaos lusuh, tapi hati penuh semangat menjaga sistem pengetahuan kita. Kita tetap menjadi kota yang tidak tumbang, justru karena tahu caranya bersandar satu sama lain. Dalam istilah Emile Durkheim, ini disebut solidaritas kolektif. Tapi bagi kita, ini adalah makan sama-sama di bale-bale, minum pada sloki yang diberi ke satu orang dan bergantian seterusnya, antar sayur ke rumah sebelah, juga peluk diam-diam saat duka datang, termasuk ikut menonton PostMan dan seniman asal Maumere lainnya berkesenian.
Kupikir, ini adalah fondasi lainnya, menjadikan Maumere adalah tubuh yang dibentuk juga oleh solidaritas warga.
Penutupan Maumerelogia 5 bukan hanya panggung tapi sebuah cermin, aku melihat Maumere, bukan sebagai kota yang menunggu menjadi “besar” tapi jika kita cukup berani memandangnya tanpa inferioritas, ia tampak utuh dengan keunikannya sendiri. Kota yang tahu bahwa kekuatannya ada pada akar yang tumbuh dari ingatan bersama dan batang yang tegak oleh kasih antar warganya.
“Deeper the Roots, Stronger the Tree” selesai didendangkan. PostMan menutup sesi mereka dengan lagu yang magis, kupikir. Bersama mereka dan generasi yang dianggap melupakan masa lalu, aku yakin bahwa kita tidak benar-benar lupa, kita hanya sedang belajar untuk menyambung akar dengan jaringan Wi-fi, menulis ulang sejarah dengan bahasa baru, meneruskan warisan dengan cara-cara yang kreatif. Kemudian pada suatu malam, mungkin di panggung festival Maumerelogia edisi berikutnya, kita akan kembali mendengarkan “Deeper the Roots, Stronger the Tree“ bukan cuman sebagai lagu tapi doa yang menjelma sebagai melodi.













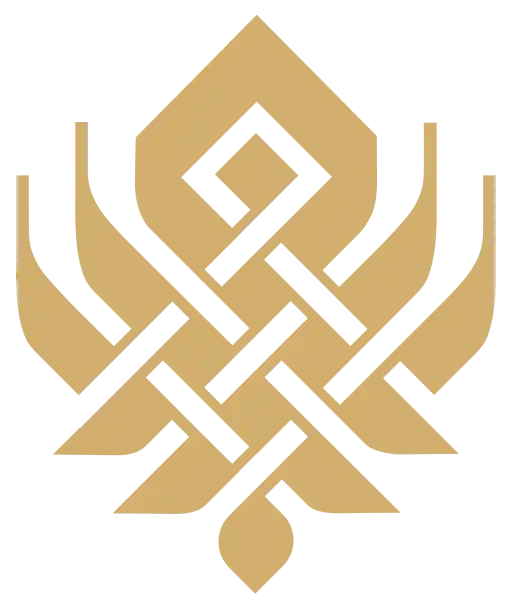


Deeper the Roots Stronger the Tree!