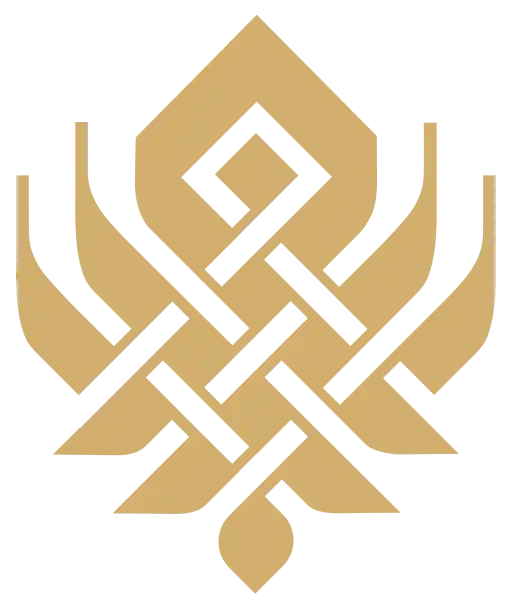“Apa kata Makassar kepada Jakarta yang membuatnya tiada?”
Sebuah kalimat dilemparkan seperti batu kecil ke danau sunyi, memercikkan kenangan, menyibakkan gelombang-gelombang kecil yang menjalar diam-diam ke pusat kesadaran. Kalimat itu bukan jawaban, melainkan realitas yang berbicara.
Di antara rak-rak buku yang bersandar tenang di Gramedia Maumere, suara-suara dari tubuh Makassar dibacakan oleh tubuh-tubuh lain di Maumere dalam acara Temu Sapa bersama Aan Mansyur, penulis dan penyair Indonesia berdarah Bugis, Kamis, 10 April 2025.
Mereka tidak sekadar membacakan puisi, Makassar pun menjelma lebih dari sekadar peta, lebih dari garis pantai dan poros jalan; ia menjadi metafora dari seseorang. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari aku, kamu, dan dia.
Lalu, jika Makassar adalah jawaban, kemudian apa pertanyaannya ?
Mungkin: Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh bahasa ibumu sendiri?
Atau: Apakah kau masih kota, jika puisimu tak lagi ditulis dalam lidahmu?
Metafora tentang Makassar dalam puisi tersebut mengajak kita untuk melihat kota kita sendiri-Maumere. Kita dibawa menengok ke belakang, bukan karena terjebak masa lalu, tetapi karena ingin tahu bagaimana tubuh ini disusun. Tubuh kota, tubuh bahasa, tubuh kitai sendiri.
“Saya adalah produk kolonialisme.”
Kalimat ini muncul dalam sharing bersama Aan, menggema seperti sesuatu yang tidak bisa lagi ditolak. Kita belajar bahasa dari sinetron, belajar gaya bicara dari iklan, dan menyebutnya ‘modern’. Kita menamai diri dengan huruf kapital yang tak kita mengerti, lalu perlahan-lahan melupakan aksara ibu.Kalimat itu menyoroti bagaimana bahasa, sebagai warisan dan sekaligus medan pertempuran, membentuk cara berpikir masyarakat. Bahasa sinetron dan iklan telah menggantikan “ lidah Ibu”. Kota-kota yang pernah kuat dalam identitas kini diam-diam berpikir lewat lensa orang lain.
Kita dikolinialisasi untuk mengadopsi, menyerap, menyamar, menyelamatkan diri lewat penyeragaman. Tapi dalam proses itu, kita kehilangan bentuk asli kita. Menjadi seperti lagu jalan berlubang milik mendiang J.E.Papache yang hingga akhir lagu, liriknya tidak pernah memberitahu kita bahwa perjalanan melewati jalan berlubang itu seolah belum sampai pada momen tiba: ia bergerak, tapi tak sampai; ia mencatat, tapi tak mengenali siapa yang dicatatnya.
“Untuk menjadi penyair, penulis, seniman, adalah bersedia masuk ke ruang tak pasti. Itu baik jika kita menyadari kita tidak tahu, dan itu baik-baik saja.Dengan ketidaktahuan itu kita berusaha belajar agar tahu, “ ujar Aan Mansyur menjawab kembali tanggapan dari seorang audiens tentang bagaimana menjadi seorang penulis.
Lanjutnya, “Sekolah membuat kita memuja mereka yang bisa menjawab, bukan yang bisa bertanya. Kita tidak suka mempertanyakan sesuatu, termasuk tentang diri kita sendiri, karena itu meresahkan dan kita tidak suka resah. Kita tidak suka hal-hal yang tidak pasti.“
Pernyataan Aan ini terdengar seperti sebuah ajakan untuk berani “membedah” tubuh sendiri termasuk kota kita dan menemukan kenyataan-kenyataan yang membuat kita gusar, peka akan kondisi sesama dan mengambil langkah yang bisa membawa dampak. Sebab kita sendiri ada sekumpulan aku, sekumpulan dia, sekumpulan kita yang membentuk bagaimana rupa tubuh kota kita. Maka pertanyaan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang menyingkap sejarah, identitas kita yang terpendam.
Aan Mansyur, dalam puisinya juga pernah menulis:
“Kota yang baik adalah kota yang menampung semua kenangan, bahkan yang tak ingin dikenang.”
Mungkin itulah Makassar sekaligus Maumere malam itu. Ia adalah tubuh yang terluka namun tetap berdiri, suara yang sempat dibungkam namun kini bernyanyi lagi. Dan Jakarta, barangkali hanyalah nama lain dari kecepatan, dari ambisi, dari keterasingan yang dibungkus impian. Dan ketika acara ditutup dengan pembacaan puisi dari buku Aan yang akan datang, kami tahu: kota-kota akan selalu memiliki cara untuk bicara, selama kita masih bersedia menyimak, mempertanyakan dan menemukan akar identitas kita yang tercerabut oleh aneka bentuk penjajahan.
Lalu, bagaimana puisi tentang Maumere akan ditulis?
Satu yang pasti, (kita berharap) Maumere kini sedang menulis dirinya sendiri.
Bukan dengan tinta yang dipinjam dari sistem pengetahuan lain, tapi dengan darah, napas, dan bahasa yang ia temukan di bawah kakinya sendiri, tempat ia berpijak pada jati dirinya yang asali, pada sejarah dan kebijaksanaan para pendahulu, pada tradisi yang sebagian besar adalah bahasa perlawanan terhadap warisan-warisan penjajahan lainnya.