Di sekitar patung Teka Iku, anak-anak berdatangan memegang teks di tanganya, lampiran puisi, serta mulut yang terus bergerak membaca dan melihat kembali puisi yang mereka baca. Suara sound yang sudah dipersiapkan, menjadi lantunan untuk menunggu giliran membaca.
15 Mei, Maumerelogia menghadirkan satu platform dengan tajuk “Sore Puisi, Maumere dan pertanyaan yang mengikutinya”. Ada tiga sekolah yang berpartisipasi, dari SMA Negeri 1 Maumere, SMA Negeri 2 Maumere, juga SMK Bhaktyarsa. Forum ini difasilitasi oleh kelompok Bohemian Club yang membuka forum secara internal dengan masing-masing sekolah dan membuat kurasi bersama atas penulis-penulis, juga puisi yang akan dibawakan.
Forum ini hasil dari proses kurasi selama satu bulan dan latihan intensif dua minggu bersama siswa-siswi yang tertarik untuk membaca dan merayakan puisi. Kurasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan kecil antaranggota, guru pendamping, dan tim Bohemian Club. Proses ini bukan hanya memilih puisi, tetapi juga membicarakan kenapa puisi-puisi itu penting untuk dibacakan hari ini oleh anak-anak Maumere.
Masing-masing sekolah memilih nama-nama penulis yang puisinya akan dibacakan. SMK Bhkatyarsa, memilih membacakan puisi-puisi dari Erich Langobelen, Mario F. Lawi, Tia Ragat, juga Ika Arundati. Dari diskusi teman-teman Bhaktyarsa, mereka ingin fokus pada penulis dari NTT, untuk melihat bagaimana puisi-puisi itu membicarakan atau merekam “kampung” atau ‘Rumah” dalam setiap bait-bait puisi yang mereka ciptakan.
Ada 5 Puisi Erich Langobelen . Ada Epistola, Somiboladere, Di Nuba Nara, Ave Maria, dan Leva. Melalui puisi-puisinya, Erich menunjukkan bahwa kampung adalah tempat keberanian dimulai—bukan karena ia sempurna, tapi karena di sanalah luka bisa dirawat, doa bisa didengar, dan sejarah bisa ditulis ulang. Dalam dunia yang terus bergerak cepat dan terancam melupakan akar, puisi Erich mengajak kita untuk melambat, mendengar, dan mengambil jarak tetapi juga tetap terikat, dan berkata: “biarkan kami hidup dari doa seorang perempuan tak dikenal itu.”- (penggalan puisi Ave Maria)
Dari Mario Lawi, ada 4 puisi yang dibacakan. Ada Matria, Pulang, Lahir, dan Naik. Dalam puisi-puisi tersebut, Mario Lawi mengajak melihat agama ketika bertemu dengan tanah—dengan sirih-pinang, cengkih, malaikat, dan litani nenek yang penuh kasih. Penyair menunjukkan iman bukan sebagai wacana transenden, tapi juga sebagai pengalaman tubuh.
Ada juga puisi-puisi dari Tia Ragat dan Ika Arundati yang membicarakan tentang cinta, keluarga, serta segala personal tentang kerinduan tentang rumah yang terus terhimpit kota dan kata cinta yang kandas dalam penantian.
Dari Bhaktyarsa, ada Mikaela B. Defilci, Theresia M. Candrawati, Katarina Ito Fila, Yuliana K.J. Langoday, Reginaldis M. Surung, dan Adrianus Dhena yang membacakan puisi.
Penampil dari SMK Yohanes Paulus 2 memilih untuk fokus pada karya puisi dari Chairil Anwar sebagai salah satu pelopor angkatan 45. Ada beberapa puisi yang dibicarakan, di antaranya Karawang Bekasi, Aku, Cintaku Jauh di Pulau, Cerita Buat Dien Tamaela, Kepada Peminta-minta, Kepada Kawan, Selama Bulan Menyinari Dadanya, Isa, Senja di Pelabuhan Kecil, juga Sebuah Kamar.
Dalam teks kurasi puisi yang disusun Bohemian Club bersama teman-teman dari SMA John Paul II Maumere, beberapa puisi yang dipilih ini adalah cermin dari pergolakan jiwa seorang anak muda di tengah gejolak zaman. Ia menulis tentang perjuangan dan pengorbanan dalam puisi seperti Karawang-Bekasi, mengangkat suara para pejuang yang gugur namun belum selesai tugasnya.
Melalui Aku dan Kepada Kawan Chairil menyuarakan pemberontakan eksistensial—ia ingin bebas, menolak tunduk, dan melampaui kematian. Di sisi lain, dalam Cintaku Jauh di Pulau dan Senja di Pelabuhan Kecil, tampak sisi melankolis dan rindu, menggambarkan cinta yang terpisah oleh jarak dan ajal.
Kematian, sebagai tema utama, hadir tidak hanya sebagai akhir hidup, tetapi juga sebagai ruang tanya dan perenungan. Puisi Isa dan Selama Bulan Menyinari Dadanya menunjukkan kedalaman refleksi spiritual dan kehilangan masa kecil. Melalui Cerita Buat Dien Tamaela, Chairil juga menyentuh identitas budaya lokal, menghidupkan kekuatan alam dan mistik nusantara.
Singkatnya, puisi-puisi Chairil Anwar mengalir dari semangat perjuangan, gejolak batin, cinta yang tertunda, hingga pertanyaan tentang hidup dan mati—dengan bahasa yang jujur, tajam, dan menggugah.
Ada Makrina Destrada Dui, Shalom Hosanna Nau, Cherish Metanoia Nau, Maria Agustina Mecilia Punga, Marselinus Marstelo Lande, teman-teman dari SMA John Paul II yang membacakan puisi.
Teman-Teman SMA Negeri 1 Maumere, membacakan puisi-puisi karya Norman Erikson Pasaribu, Cynta Hariadi, Mariati Atkah, dan Aan Mansyur. Ia dan Pohon” & “Aubade” karya Norman, menyuarakan keresahan dan harapan kaum queer. Kota menjadi simbol tempat yang ambigu—perlindungan dan penolakan bercampur. Pohon dan ruang publik menjadi metafora akan cinta yang tersembunyi dan solidaritas yang sunyi. Layar Lebar” & “Jarak” karya Cynta Hariadi menceritakan peran ibu sebagai pelindung dan penghibur. Imaji benda-benda rumah tangga disulap menjadi dunia dongeng, penuh magis dan kasih. Rumah menjadi ruang perlindungan dan kenangan masa kecil.
puisi Mariati, Kematian Seorang Pemburu” dan “Pulang Kampung” menghidupkan kembali suara perempuan dan alam. Ia menelusuri sejarah manusia yang tersembunyi dan menyoal hubungan manusia dengan tanah, kampung. Puisi-puisi Aan, menyentil kehidupan modern yang absurd dan penuh tekanan. Dari warung bakso hingga sistem kerja yang eksploitatif, puisinya mengajak pembaca mempertanyakan realitas sosial. Ia menyinggung bagaimana negara, kapitalisme, bahkan mimpi, mengatur kehidupan.
Yulita Rosalia, Mikhael Nautillus Christian Botha, Chiara Alfridtri Da Delang, Mauritzia Grasela Putri, dan Abraham Leonard Nyongki, tampil membacakan puisi.
Semua penyair membawa suara yang jarang didengar: queer, perempuan, kaum tertindas, rakyat kecil. Melalui puisi, mereka menawarkan ruang baru: untuk merasa, mengingat, dan melawan. Kota dan tubuh menjadi ruang perlawanan.
Puisi-Puisi ini dibacakan bergantian, tidak lupa juga dengan penampilan dari Mof Mofers Girl, dan pembacaan puisi dari Mahasiswa Muhammadiyah Maumere. Momen pembacaan puisi menembus waktu, matahari sudah terbenam, tetapi suara-suara itu belum berhenti. Lampu senter dinyalakan, menemani pembacaan puisi hingga selesai.
Platform ini menunjukkan bahwa sastra bukan milik segelintir orang, tapi bisa tumbuh di ruang sekolah, di tangan anak muda, di kota seperti Maumere. Di balik tiap pembacaan, ada proses belajar—tentang memilih, memahami, dan menghidupi kata. Yang terjadi bukan sekadar acara seni, tapi cara baru membangun ekosistem berpikir, merasakan, dan terlibat. Dari sini, muncul harapan: bahwa ruang-ruang semacam ini akan terus bertumbuh, lintas waktu dan generasi.













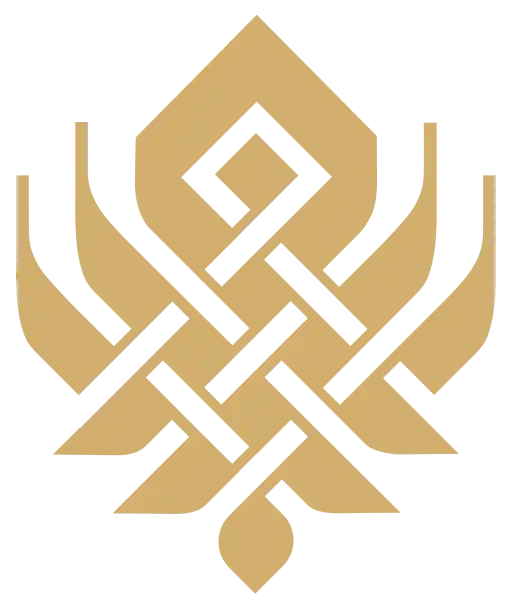


Acara seperti ini harus rutin digelar. Terima Kasih Maumerelogia