Panggung pertunjukan, terutama teater, tak pernah hanya menyajikan diksi. Ia menyulut diskusi. Dengan keyakinan semacam itu, panggung adalah bentuk lain dari tungku api: sekalipun telah padam api, siapa pun yang terpapar merahnya akan ikut membara, tapi juga bisa terbakar, terutama bila tak cukup kuat mengukur dan mengontrol jarak darinya.
Demikian pengalaman yang saya rasakan ketika panggung pertunjukan Maumerelogia 5 berakhir. Tepuk tangan dari para penonton justru menjadi tanda bahwa percakapan baru saja dimulai. Bukan hanya sekali, tapi bisa berulang kali dalam beberapa babak, dengan spektrum pembacaan yang tak pernah tunggal.
Tulisan ini barangkali adalah babak lanjutan dari percakapan dimaksud, secara khusus menyinggung bagaimana pertunjukan The Brief History of Dance (TBHoD) menghadirkan tegangan pembacaan dalam diri saya, bahkan menghasilkan sesuatu yang lebih jauh dari itu.
TBHoD adalah pertunjukan kolaboratif yang digarap oleh Ari Dwianto bersama Studio Teater KAHE. Karya ini dipentaskan pada Senin, 19 Mei 2025 di Aula Rumah Jabatan Bupati Sikka.
Pertunjukan dimulai dengan menghadirkan enam aktor yang berbaris sejajar, berdiri menghadap penonton dengan gestur yang relatif kaku. Tubuh polos dan tegap di bawah cahaya sepia, kaki yang bertumpu pada titik yang stagnan, dan langkah yang terkunci tanpa banyak gerakan menjadi koreografi dasar sepanjang pertunjukan.
Sekilas hal tersebut bisa bertentangan atau membingungkan penonton yang mungkin saja sudah terlanjur berharap pada judul pertunjukan tersebut, yaitu akan menyaksikan bagaimana sejarah tari terbentuk dari zaman ke zaman dengan berbagai dimensi gerakannya dipentaskan dalam sebuah panggung teater.
Namun, THBoD bukan sekadar tentang bentuk dan gerakan sebagaimana pertunjukan tari yang sering dibayangkan. Riwayat tari dalam THBoD tidak berhenti pada bagaimana lekuk badan dan langkah bertautan dengan ketukan nada atau musik.
Riwayat tari dalam THBoD adalah riwayat ketubuhan manusia dalam merespon dan membentuk dunia: mulai dari pengalaman akan nama, makanan, tempat tinggal, lingkungan pergaulan, mitos, cita-cita, hingga bagaimana ada kesadaran untuk mengidentifikasi membentuk kembali identitas yang otonom.
Tak heran, formasi yang kaku dari koreografi THBoD bisa dibaca secara simbolik bahwa manusia selalu tak pernah bebas dari problem ketubuhan. Selalu ada yang tak bisa lepas atau bebas dari kepatuhan terhadap kekuasaan, entah melalui institusi pemerintahan, agama, budaya, kelompok sosial, arisan, lingkar pertemanan, hingga keluarga dan rumah yang dengan satu dan lain cara selalu dapat mengintervensi sampai jauh ke dalam pengalaman ketubuhan orang per orang.
Karena itu, pertunjukan yang berlangsung sekitar 120–an menit ini lebih banyak menempatkan para aktor untuk bercerita tentang irisan-irisan pengalaman di atas. Masing-masing mereka diberi ruang yang sejajar untuk bercerita sebanyak-banyaknya dengan satu benang merah: siapakah saya?
Saya dalam semesta pertunjukan TBHoD adalah Michael Eduard Gaja Seto (Megs), Yenti Andriana Nino (Yenti), Andreas Sudirman Moan Laju (Silvy Chipy), Kristina Beatrix Tethy Nong Goa (Qikan), Yasinta Aprilia Carmela Mude (Intan), dan Hironimus Huku (Rizal).
Dengan lugas, Megs dan kelima aktor lain bercerita secara bergantian. Semua selalu terlebih dahulu memperkenalkan kembali namanya––seakan pengenalan akan nama adalah pengenalan akan babak-babak dalam riwayat hidup––sebelum bercerita tentang usia, alamat, kebiasaan, grup band kesayangan, film, tokoh radio, artis kesayangan, hobi, pendidikan, hantu di gang rumah, hingga kesadaran akan gender yang lama terbungkam.
Beragam pengalaman personal maupun kolektif yang dibagikan menekankan secara kuat signifikansi perbedaan komposisi latar yang membentuk mereka.
Dalam momen yang demikian aktor tidak hanya bercerita tentang hal yang menyenangkan, tetapi juga menyajikan kisah-kisah penderitaan dari ruang ”privat.” Yang sensitif, yang penuh luka, dan yang traumatik bahkan yang sering dianggap ”memalukan”, misalnya tentang orientasi seksual atau kesadaran gender, dibagikan dengan benderang dan tanpa beban sebagai konsumsi publik.
Di situ batas antara yang privat dan yang publik, yang personal maupun yang komunal, yang tabu atau pun yang perlu, mengalami proses redefinisinya: dibongkar dan dirumuskan kembali.
Yang menarik adalah semua narasi yang ditampilkan dalam TBHoD tidak sekadar jatuh dari jagad rekaan atau alam imajinatif sang sutradara, tetapi justru merupakan hasil eksplorasi pengalaman riil dari masing-masing aktor yang dipertajam bersama sepanjang masa residensi dan persiapan.
Posisi sutradara dalam pertunjukan ini hanya serupa fasilitator yang memantik memori, menyusun plot, dan memastikan lalu lintas penceritaan, tanpa pernah merekayasa semua lampiran pengalaman yang telah dipilah dan dipilih sendiri secara bebas oleh aktor––sesensitif apapun ceritanya, telah mendapat semacam persetujuannya (konsensus) untuk ditampilkan ke panggung.
Apakah hal yang demikian membuat posisi sutradara jadi tak berarti? Justru sebaliknya, Ari Dwianto justru berhasil menavigasi sebuah panggung pertunjukan menjadi ruang terapi kolektif.
Dengan kepekaannya memilih aktor, kelenturannya merumuskan pertanyaan pemantik dalam naskah awal, mengontrol jarak ”pembacaan,” terutama ketelitiannya mengatur plot, maka THBoD bisa dihadirkan bukan hanya sebagai sebuah seni pertunjukan yang dapat beresonansi dengan pengalaman penonton, tapi terutama menjadi ruang lain yang berfungsi sebagai sarana penguatan identitas serta jembatan komunikasi antara aktor dan penonton, antara masa lalu dan masa depan, antara memori dan imajinasi, antara penolakan dan penerimaan, serta antara luka dan peluang kesembuhan.
Dalam momen yang demikian saya membayangkan Ari Dwianto adalah konselor berkedok sutradara. Sementara itu, THBoD adalah metode yang ia siapkan untuk memberi konseling dalam kemasan yang paling menyenangkan dan tentu saja reparatif. Tak heran THBoD mampu memberi ruang dan kesempatan bagi Andreas Sudirman Moan Laju, satu dari keenam aktor, mengalami semacam momen pembesasan, keluar dari kedok masa lalunya, dan memperkenalkan ”sejarah” baru bagi tubuh dan identitas dirinya sebagai Silvy Chipy. Semua terjadi di atas panggung sedemikian lugasnya, sedemikian berterimanya.
TBHoD akhirnya berhasil menyuarakan lebih dari sekadar memori. Ia sebenarnya sedang membentuk terapi kolektif: ruang untuk merasa tanpa takut, berbicara tanpa dihakimi, dan pengakuan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dalam sunyi, melainkan ”dirayakan” secara bersama. Di ujung sana ada cerita lain yang menanti.
Penulis: Erich Langobelen












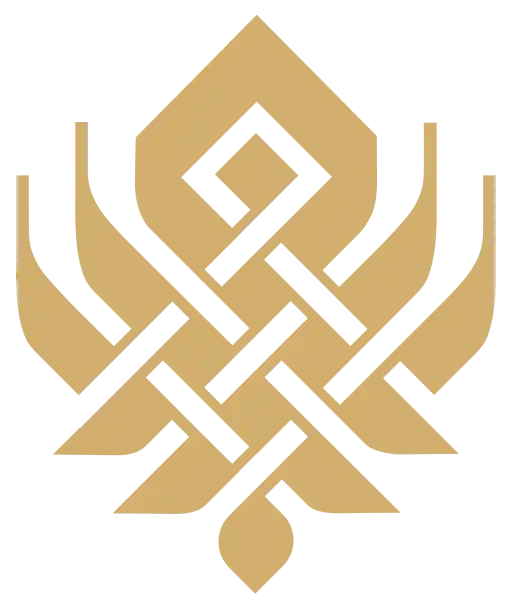

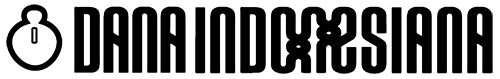
🫂🫂🫂🫂🥰🥰🥰🥰🙏🙏