“Yes, I’ve been a bad guy, been higher than the blue sky
And the truth is I don’t wanna die an ordinary man…”
— Ozzy Osbourne, Ordinary Man
Mendengar lagu Ordinary Man dalam keheningan malam setelah hari-hari panjang di Maumere, aku merasa seolah Ozzy sedang duduk di sebelahku, memetik gitar dalam sunyi jalan-jalan kota yang mulai padam, menyanyikan tentang kehampaan, kehilangan, dan harapan yang tersisa di saku-saku warga biasa.
Di tengah alunan suara tua itu, aku membayangkan Maumere sebagai panggung pertunjukan yang dihidupi oleh orang-orang biasa—yang tidak sempurna, tidak selalu menang, tetapi terus berjalan.
Kami, orang-orang yang memilih pulang meski jalan penuh lubang, bukanlah pahlawan dengan narasi besar. Kami hanya orang biasa yang kadang tersesat di simpang antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang belum tentu. Tapi kami belajar berdansa di atas lubang-lubang itu—sebagaimana lagu Papache dulu diputar keras di oto kayu, guncang tapi dekat, asing tapi akrab.
Di festival Maumerelogia 5, aku menyaksikan banyak bentuk “keberanian orang biasa.” Seorang waria dari Perwakas berbagi kisah hidupnya dalam tawa dan tangis yang nyaris bersamaan. Mahasiswa yang gugup membacakan risetnya soal monopoli tanah oleh misi kolonial di Nangahale. Seorang ibu dari pesisir yang menceritakan bagaimana suara gelombang laut bukan hanya bunyi, tapi juga bahasa roh para leluhur. Mereka semua—dalam cara masing-masing—menolak menjadi “manusia biasa” yang dimaknai sebagai diam, tunduk, atau lupa.
Ozzy menyanyi dengan luka dan bangga yang bersamaan. Dan di Maumere, kami juga belajar menerima luka sebagai bagian dari identitas kota. Luka kolonial yang belum sembuh, trauma pembantaian 65 yang masih bergema dalam keheningan warga, dan kerinduan akan spiritualitas yang terpisah dari alam.
Tapi kami juga punya melodi kota yang menyembuhkan. Musik, tawa anak-anak di jalan, bahkan riuh pasar saat pagi masih buta. Ritme ini adalah ritme umpan balik—yang tidak hanya bergerak ke depan, tapi juga mundur dan berputar, mengingatkan, menegur, dan memberi arah baru.
Maumere adalah koreografi sosial yang tak selesai. Seperti lirik Ozzy: “I was unprepared for fame, then everybody knew my name”, kota ini kadang tak siap menjadi sorotan—dalam lensa pariwisata, pembangunan, bahkan ekspektasi nasionalisme. Tapi kota ini tetap berjalan. Di balik gereja tua, pasar malam, atau kantor bupati, selalu ada cerita—yang bukan tentang sukses, tapi tentang bertahan. Tentang menjadi diri sendiri di tengah hasrat yang dikurung norma.
Koreografi kami adalah koreografi jalanan, bukan panggung. Kami menari dengan tubuh penuh debu, berpeluh di aspal yang mengelupas. Kami tahu, jalan pulang bukan rapi beraspal. Kadang harus guncang dulu untuk saling mengenal, saling tatap, dan saling percaya bahwa dari jalan berlubang, cinta dan solidaritas bisa tumbuh. Terima kasih, jalan berlubang.
Maumerelogia tidak sedang menampilkan pertunjukan yang utuh. Ia menawarkan fragmen. Seperti hidup orang biasa yang disusun dari potongan-potongan kenangan, cita-cita kecil, dan pilihan yang tak pernah hitam-putih. Karya seni di festival ini bukan sekadar untuk ditonton, tapi untuk diselami—sebagai percikan, bukan jawaban.
Ozzy bilang, “Don’t forget me as the colors fade…” Dan aku rasa, kami tidak akan lupa. Maumere bukan hanya ruang, tapi ingatan. Bukan hanya kota, tapi ibu. Dalam gelombang globalisasi dan bayang kolonialisme yang masih menjuntai, kami kembali mendengar bahasa ibu; bahasa yang tidak sekadar dituturkan, tapi dirasa. Di jalan-jalan kota ini, kami menggali sejarah bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai kemungkinan masa depan.
Aku tidak ingin jadi manusia biasa yang diam di tengah kekacauan ini. Kami tidak ingin Maumere jadi kota biasa yang hanya menjadi panggung bagi investasi, konflik identitas, dan janji-janji kosong dari dunia modern. Kami ingin tetap berjalan, bahkan ketika jalannya berlubang. Karena dalam lubang itulah, kami menemukan satu sama lain.
Dan mungkin… Menemukan rumah.
Ada jeda sunyi setiap kali pesta selesai. Lagu berhenti diputar, tenda-tenda dibongkar, dan suara-suara itu kembali mengendap jadi debu di antara jalan-jalan kota. Seperti selepas Maumerelogia. Kota ini sejenak terasa seperti panggung, tempat segala yang disembunyikan menjadi mungkin untuk diceritakan. Tapi kemudian, lampu padam. Dan ruang itu jadi kosong.
Maumere hari ini, dalam sorotan dan bayang-bayangnya, menghadirkan semacam kegelisahan eksistensial. Sebuah kota pascakolonial yang menyimpan terlalu banyak lubang—baik pada jalanan maupun pada ingatan kolektifnya.
Di satu sisi, ada semangat untuk merebut narasi, menyulam kembali jaringan sosial, menciptakan kanal-kanal suara yang lahir dari tubuh-tubuh yang selama ini dibungkam. Di sisi lain, ada kekosongan, semacam kehampaan setelah momen euforia, seperti panggung kosong sehabis pertunjukan.
Maumerelogia mengingatkan kita bahwa kota bukan hanya sekumpulan bangunan atau kebijakan tata ruang. Ia adalah lanskap emosi, trauma, dan harapan. Ia adalah ruang antara—antara kenangan dan utopia, antara tanah yang digenangi air dan tubuh yang menari di atasnya.
Namun kita tahu, pertunjukan harus usai. Dan kota harus kembali pada kesehariannya.
“When the lights go down, it’s just an empty stage”
(Saat lampu padam, yang tersisa hanyalah panggung yang kosong)
— Ozzy Osbourne, Ordinary Man
Dan mungkin dari ruang kosong itulah, segalanya bisa mulai lagi.









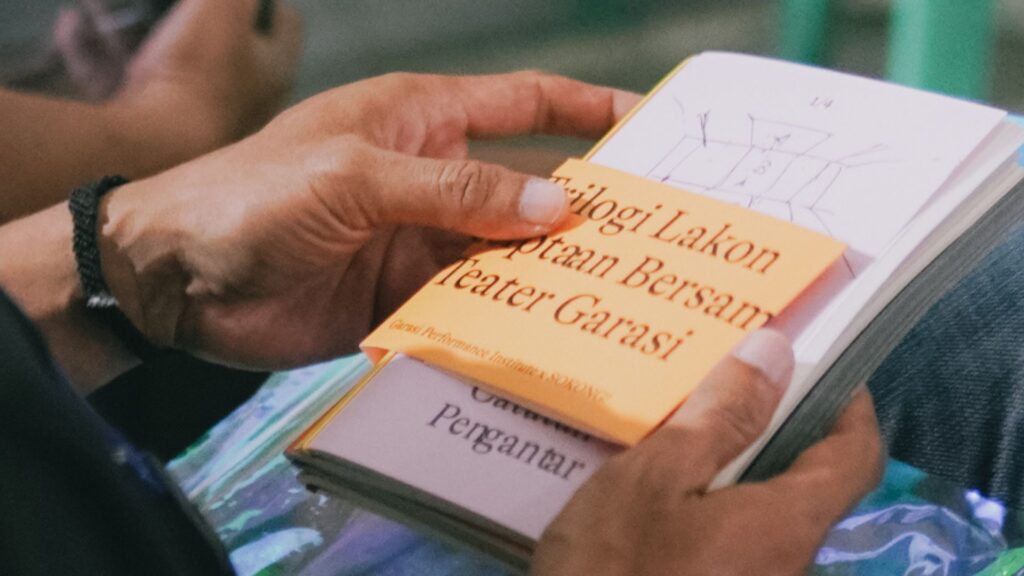












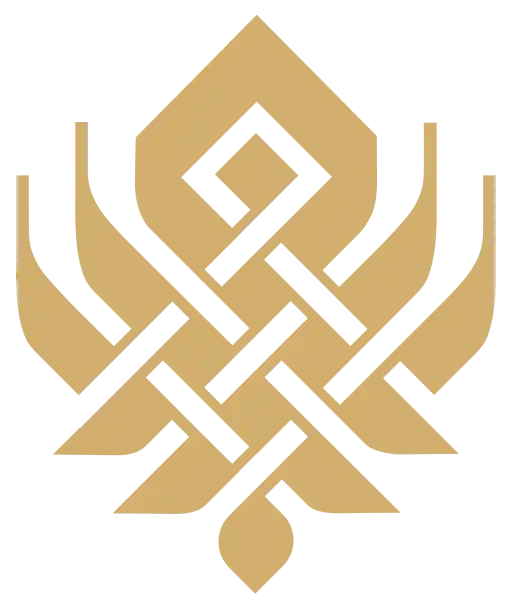


Menyala sekali tulisan ini….izin posting Maumerelogia