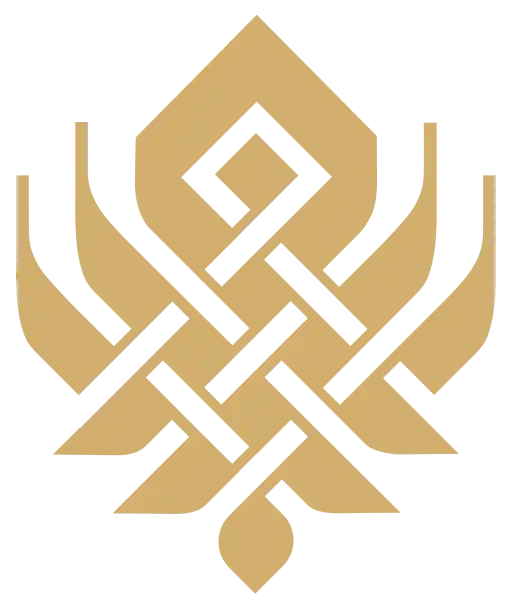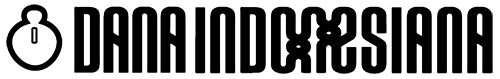jalan, jalan berlubang!
: dan nada-nada yang (pernah)
tumbuh dari mulut Ibu
Kata Kunci: kultur, kota, kita dekolonisasi, rekonstruksi ruang, ritme umpan balik, jalan pulang, kanal-kanal, hasrat/gairah, koreografi sosial
Jalan Berlubang adalah judul salah satu lagu yang diciptakan oleh Papache, seorang musisi dan produser musik Maumere yang karya-karyanya santer beredar di awal tahun 2000-an. Dalam lagu itu, Papache bercerita tentang seorang pria yang ketemu dengan seorang wanita di sebuah bus kayu jurusan Kampung Nilo – Nirangkliung (Kabupaten Sikka). Jalan berlubang sepanjang jalan pulang kampung di satu sisi membuat perjalanan terasa sangat sulit dan menyakitkan. Namun, kondisi itu juga menciptakan romansa di antara keduanya, yang terpaksa harus mengalami pengalaman perjalanan yang penuh guncangan, saling berdesakan, makin dekat, saling lirik, hingga berkenalan: “terima kasih jalan berlubang!”
Sebagaimana lagu-lagu Papache lainnya yang lucu dan jenaka, lagu ini disambut dan dirayakan oleh warga, diputar di tenda-pesta, di radio dan di angkot-angkot. Album-album Terminal yang diproduksi oleh Papache menjadi pelipur lara, mengiringi masa awal perubahan rezim Orde Baru ke Reformasi, menemani warga mengalami krisis moneter yang mencekik dengan ‘perayaan-perayaan kecil’ khas orang Maumere.
Hari-hari ini, mendengarkan jalan berlubang memantik spektrum gagasan mengenai Kultur, Kota, Kita kini, dengan seluruh konteks Maumere yang makin kompleks soalnya, sebagaimana Indonesia yang kian gelap dan dunia yang secara terang-benderang mempertunjukkan polarisasi dominasi serta kuasa dalam aneka model kolonialisme tempatan dan politik ekonomi neoliberal yang mengglobal. Sebagaimana Indonesia, Maumere hari ini jarang sekali dilihat dan dimaknai sebagai tempat dan ruang pascakolonial yang mewarisi lubang-lubang akibat kolonialisme: kenyataan politik identitas, dinamika negara – agama yang dominan dan tak sepenuhnya berhasil membangun sistem nilai serta norma, juga sistem ekonomi yang kian terkapitalisasi.
Generasi Maumere dari masa ke masa mencoba ‘membangun jalan-jalannya’ masing-masing, tak pernah sungguh-sungguh berupaya menyadari lubang-lubang itu, dalam satu dan lain momen terjebak di dalamnya, kerap tersesat oleh laku mengejar masa depan yang antah berantah sembari dihimpit masa lalu yang tak sepenuhnya dikenali. Diskursus dalam Maumerelogia 5 tahun ini berjangkar pada tegangan-tegangan identitas kota pascakolonialitas semacam ini yang kemudian direfleksikan sebagai jalan pulang, pada jalan berlubang:
sebuah upaya memulai refleksi dan gestur dekolonisasi, dengan pertama-tama menyelidiki kota Maumere hari ini, seluruh sejarah dan rancang bangunnya di masa depan, dan dinamika kewargaannya yang terus menghidupi tradisi serta modernitas yang datang bersama proses globalisasi.
Sebagai sebuah festival kota yang menempatkan kesenian sebagai kajian tentang masyarakat, Maumerelogia 5 menghadirkan spektrum praktik sosial dan presentasi seni, galeri alternatif dan peristiwa pertunjukan, pengelolaan ruang publik dan ruang-ruang spesifik seperti kampus dan kantor pemerintahan, aktivitas-aktivitas di jalan dan forum-forum diskusi sebagai bagian dari upaya membangun dialog kritis antar sesama warga masyarakat. Secara programatik, ide besar Maumerelogia 5 diterjemahkan dalam forum gagasan, pertunjukan musik dan teater, pameran, serta pengarsipan lewat catatan-catatan proses.
Forum Gagasan: ‘Naik Oto, Pulang Kampung’
Forum Gagasan dalam Maumerelogia 5 melihat dari dua bola mata: yang politis dan yang estetis dalam membaca kelindan kedua wawasan tersebut dalam fenomena-fenomena juga lanskap kenyataan Maumere, Indonesia dan dunia hari ini.
Kedua mata ini pertama-tama berupaya mengenali kembali jalan pulang ke kampung: melacak kembali tradisi dan sejarah, menelisik langgam modernitas yang tampak hari-hari ini dan mengintip kemungkinan-kemungkinan intervensi di masa depan yang terus bergerak. Sistem produksi kerja upahan (spesialisasi kerja), obsesi pada pengumpulan kapital, terputusnya relasi spiritual masyarakat dengan alam, persoalan perampasan tanah, perdagangan manusia, hingga politik identitas berakar pada kenyataan kolonialisme Eropa yang sulit dielak.
Kolonialisme membentuk suatu identitas kultural baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dengan kata lain sebuah ruang/waktu baru dibentuk secara material dan subjektif. Inilah yang disebut modernitas, yang berkarakter imperialis sejak awal. Forum Gagasan ingin menelisik ulang dampak-dampak kolonialisme pada penghayatan akan tradisi dan sejarah, sembari terus mencermati geliat modernitas yang terkait erat dengan pertukaran sumber daya, kerja, dan kepemilikan dalam sistem kapitalis-neoliberal; pemahaman identitas intersubjektif global; dan kendali pengetahuan yang berpusat serta tertuju pada Barat sebagai standar.
Tak sekedar meniti jalan pulang ke kampung, Forum Gagasan juga dirancang supaya publik bisa merekonstruksi ruang/waktu Maumere hari ini, dengan seluruh koreografi sosial, dan performativitasnya sebagai medan interaksi dan kultur/kota yang terbentuk pascakolonial. Dengan keyakinan bahwa kesenian adalah alat, cara sekaligus aksi dekolonisasi yang bisa mengintervensi masa depan (speculative intervention), forum-forum gagasan menghadirkan diskursus perihal seni, praktik dan gerakan sosial, dan mendorong partisipasi publik lewat perjumpaan artistik (artistic encounter) yang sejak awal jadi salah satu metodologi Maumerelogia.
Dari riset Crossing Borders, terbaca bahwa gagasan kemajuan yang kemudian menjadi ciri masyarakat modern tidak serta merta berlaku ketika suku Bajo membangun peradaban mereka sendiri di Kampung Wuring, pesisir utara Kota Maumere. Dari riset atas arsip-arsip gereja, monopoli tanah dan aset oleh Misi Gereja Katolik sejak era kolonial justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat di Nangahale yang kemudian memicu perlawanan sampai sekarang. Tak hanya itu, dikotomi identitas warisan kolonial: Barat-Timur, Sikka-Kangae direproduksi oleh pemerintah orde baru, memuncak pada peristiwa pembantaian massal tahun 1965 dan kemudian menentukan cara masyarakat di Kota Maumere berinteraksi sampai sekarang.
Dari riset keberagaman di Kota Maumere, eksistensi Perwakas (Persatuan Waria Kabupaten Sikka) ternyata lekat dengan aktivisme sosial-kultural yang turut menciptakan masyarakat Maumere yang cukup inklusif terhadap ragam gender dan seksualitas. Jejak karya mereka bisa dilacak sejak 1980-an hingga hari ini. Perwakas juga berhasil membangun penerimaan terhadap kelompok waria di tengah masyarakat dan merangsang terbentuknya gerakan berbasis gender lainnya di NTT. Dengan demikian, dekolonialisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan-perjuangan, pergerakan-pergerakan dan aksi-aksi translokal dan interlokal semacam ini untuk merombak warisan dan relasi berkelanjutan dari desain global dunia modern/kolonial.
Atas dasar itu, Forum Gagasan memilih banyak bentuk pendekatan umpan balik antar seniman, peneliti, mahasiswa, akademisi, praktisi, komunitas dan warga. Forum ini juga akan mewujud menjadi kanal-kanal pertemuan publik Maumerelogia yang intens, dialogis, kritis dan analitis. Untuk itu, kelas (lecture), presentasi, forum, tur kota, dan workshop dalam forum ini diharapkan mampu menjadi peta jalan bagi publik Maumerelogia dalam melihat kembali apa yang (pernah) tumbuh: suatu tatanan masyarakat di Flores yang kaya akan tradisi, bahasa, pengetahuan, spiritualitas dan identitas. Sekali lagi, dan sejujurnya, jalan pulang ini tak selamanya mulus, justru, seperti lagu Papache, ada jalan berlubang yang penuh guncangan.
Panggung dan Melodi Kota: ‘Saling Baku Dempet’
Maumerelogia ingin membuka jalan tikus untuk membaca yang hari ini ditampakkan sebagai pertunjukan (is performance) dalam terminologi Richard Schechner, melalui analisis atas peristiwa kota yang hadir secara material (visible) dan diterima sebagai bagian dari yang sedang tumbuh hari ini: tata kota, jalan, gedung pemerintah, sekolah-sekolah, pertokoan, gereja, masjid, pasar, destinasi pariwisata maupun melalui upaya menghadirkan dan menyingkap apa yang ada di belakangnya (invisible) dalam ideologi, strategi, skenario dan wacana yang dirancang oleh kekuasaan: negara, agama, adat, (as performance).
Pertunjukan teater dalam Maumerelogia menawarkan kemungkinan pembacaan ulang hubungan-hubungan antara kota sebagai pertunjukan dan panggung pertunjukan, warga sebagai expert of everyday life dengan warga sebagai performer, gestur dan akting, aktor dan spektator, backstage dan front stage dalam ulang-alik lintasan paradigma as/is performance. Karya-karya yang akan ditampilkan di Maumerelogia terbentang mulai dari ragam pembacaan dramatik, tur kota, karya-karya workshop partisipatoris, karya-karya work in progress dan karya utuh.
Dalam konteks pertunjukan musik, Maumerelogia 5 hendak merayakan ‘melodi kota’, sebagai bagian dari laku merekam, mengingat, menghadirkan, dan mengudar cerita-cerita tentang kehidupan lewat lanskap suara dan bunyi. Lanskap suara dan bunyi tersebut diharapkan menjadi semacam ‘ritme umpan balik’ atas seluruh gagasan Maumerelogia. Yang kemudian dibayangkan, respons atas ritme umpan balik yang memuat pelacakan atas fenomena- fenomena sosial budaya yang ditawarkan oleh gagasan Maumerelogia dapat menimbulkan efek menyenangkan, menggetarkan, atau bahkan mengganggu kenyamanan.
Dalam merayakan melodi kota, musisi Maumere berkumpul untuk mengeksplorasi warisan kultur musik dalam ritus, pesta, ratapan dan menelusuri bunyi-bunyi di sekitaran kota Maumere. Selain bunyi, ‘suara-suara’ unik dari masing-masing musisi adalah suara warga kota yang ingin turut menyampaikan gagasan dan rasa tentang pengalaman hidup serta kewargaan mereka sehari-hari. Ruang bagi penciptaan bersama dibuka, sebagai model lain dari tradisi kulababong yang hidup di masyarakat Maumere.
Selain itu, program ini menghadirkan musisi-musisi dari luar Maumere untuk mempresentasikan karya-karya dengan beragam eksperimentasi agar dapat memperkaya wawasan, interaksi, dan referensi musik bagi para seniman dan audiens di Maumere. Pada saat yang bersamaan, kesempatan mengalami kota, kultur, dan publik Maumere, diharapkan bisa memperkaya seniman-seniman yang datang dari luar.
Perayaan ‘melodi kota’ tentu juga mendorong kolaborasi antar musisi dari beragam latar belakang praktik dan konteks budaya. Sebagaimana halnya jalan berlubang yang memengaruhi koreografi para pelintasnya, berkelok-kelok atau berguncang, para musisi dan seniman bisa saling melintasi batas-batas jalan yang dilalui. Apakah akan menghindar, melindas, menambal jalan berlubang itu, atau membuka jalan baru?
Dramaturgi Tatapan: ‘Bisa Berkenalan’
Pameran di Maumerelogia 5 menghadirkan beberapa proyek kuratorial yang menarik, yang berbincang soal tradisi dan modernitas, kuasa dan perlawanan, keragaman dan solidaritas. Karya-karya rupa yang dipamerkan di Maumerelogia meliputi karya-karya berbasis galeri, aktivasi ruang publik, pujasera, dan jalanan, serta karya-karya dengan intensi edukasi yang melibatkan partisipan pelajar dan mahasiswa. Karya-karya yang dipamerkan terbentang dari aktivasi arsip, foto, karya multimedia, dan karya-karya gambar, lukisan serta instalasi.
Spektrum karya seperti ini meluaskan cakupan partisipan dan audiens, memantik diskursus yang bisa melibatkan interaksi dalam berbagai ruang obrolan, mulai dari lingkungan-lingkungan kesenian, akademisi, komunitas dan gerakan, politik pemerintahan, dan warga dari segala bidang karya dan disiplin ilmu. Keragaman dan keluasan ruang obrolan yang dibayangkan dan ingin diupayakan ini sekaligus menegaskan karakter kajian dan artistic encounter yang ingin dibangun sebagai salah satu benchmark oleh Maumerelogia ke depannya.
Dramaturgi partisipatoris dan koreografi tatapan coba diupayakan dalam seluruh perhelatan pameran Maumerelogia 5 ini. Dramaturgi kepenontonan dipakai sebagai strategi mengorkestrasi kepenontonan aktif, mengupayakan adanya kebiasan yang dibayangkan sebagai kultur menonton pameran di Maumere dalam jangka yang lebih panjang. Sementara koreografi tatapan dalam pameran ini menawarkan ketinampilan dalam tegangan yang lazim dan spektakuler, yang biasa dan ekstraordinari, yang dekat, lekat dan berjarak. Dramaturgi tatapan juga dimaksudkan untuk memantik pertanyaan terhadap yang liyan dalam seluruh proyeksi untuk membangun ruang saling belajar, memahami, dan membangun keterhubungan entitas-entitas personal maupun sosial dalam seluruh analektika spektrum penciptaan maupun kepenontonan.
Jalan, Jalan!
Jacques Rancière menyebut bahwa kesenian dapat digunakan untuk mendorong pengalaman otonom demi menangguhkan dominasi sistem. Seni memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menciptakan ‘lanskap baru yang mungkin’ dengan menantang kategorisasi dan pandangan umum yang mapan. Estetika bisa menjadi jantung politik. Tindakan estetis adalah jelmaan dari pengalaman yang mengungkap persepsi baru dalam mengalami realitas, dan menampilkan subjektivitas politik baru yang mereklaim hak untuk berpikir, berbicara, juga bertindak, dan secara bersamaan memahami tindakan politis sebagai kemampuan subjek dalam mendistribusikan ruang politik melalui relasi sosial baru yang menantang hirarki sosial dominan.
‘Lanskap baru yang mungkin’ adalah kontribusi kesenian dalam mendorong speculative intervention, sebuah imajinasi soal masa depan, sebuah upaya menciptakan sejarah yang lebih berpihak pada pertumbuhan. Dalam gagasan eskatologi yang dikemukakan Enrique Dussel, masa depan adalah mimpi yang sebagiannya sudah mewujud hari ini, cita-cita yang sudah sedang diusahakan. Masa depan bukanlah sebuah titik final teleologis melainkan sebuah proyek yang berlangsung dalam proses analektik, ketika sejarah juga turut dibentuk oleh ragam aktor dari ragam lokasi budaya, gender, kultur, agama, dan konteks sosial politik terutama yang kerap dipinggirkan oleh dominasi kuasa maupun ideologi tertentu. Dengan demikian, eskatologi harus senantiasa berpijak dan berpihak pada yang paling miskin (option for the poor) dan menderita (option for the suffering) menuju pada sebuah realitas antar ragam (pluriverse) yang setara dan saling menyokong satu dengan yang lain dalam membangun kesejahteraan sosial-kolektif.
Dengan rupa-rupa interaksi warganya, apakah Maumere hendak berderap maju—dalam kacamata kolonialisme—menyongsong janji-janji masa depan kapitalisme global, hegemoni kekuasaan kolonial baru beridentitas Eurosentris? Atau ia membuka ruang bagi jalan pulang, jalan berlubang: kembali ke rumah Ibu, dan kembali mendengar bahasa Ibu dari mulut Ibu yang melahirkan ingatan-ingatan, tradisi, bahasa, pengetahuan, spiritualitas dan identitas yang jamak?
Jawabannya bisa jadi tak biner sebagaimana pertanyaan ini dihadirkan. Intensional maupun tidak, Kultur, Kota, Kita hari ini mewarisi kenyataan kolonialisme dengan seluruh kompleksitasnya, berkelindan dengan seluruh warisan tradisi yang mungkin tak seutuhnya dikenali. Jalan, jalan berlubang! dengan demikian adalah sebuah proposal proyek untuk kembali ke kampung halaman, mendengar bahasa Ibu, sembari terus menatap masa depan dengan seluruh distorsi globalnya, membangun masa lalu yang lebih baik untuk masa depan yang lebih lestari. Jalan, Jalan!