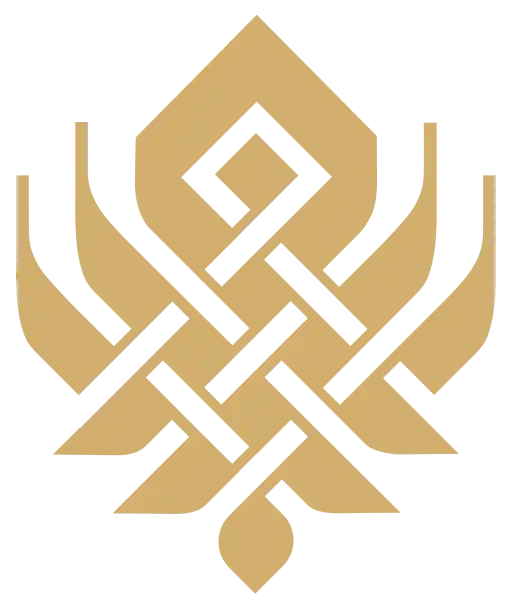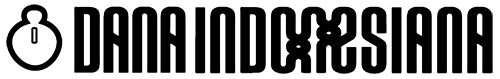Pada suatu kesempatan di hari Jumat, saya ke pasar Wairkoja. Saya menumpang mobil angkutan pedesaan, namanya oto Yesenia. Nama oto ini tidak asing bagi para pendengar kelompok musik kampung Leisplang. Ada penggalan lagu Yesenia yang menceritakan rutinitas warga yang pergi ke pasar tradisional.
regang sawe
a’u walong lema oto Yesenia
sowae du nito natok
da’a reta Watublapi
riwu lima horo bano.
Tumpangan di dalam oto didominasi oleh kaum perempuan usia paruh baya. Para penumpang berdesak-desakan. Beberapa laki-laki bergelantungan di pintu mobil. Ada pula yang memilih duduk di atas mobil. Dalam perjalanan, ada mama-mama yang makan sirih pinang. Kata mereka makan sirih pinang untuk menghilangkan mabuk. Ada yang menggerutu soal harga komoditi yang berubah-ubah.
Dari obrolan itu ada suara dari bagian bangku belakang oto yang menimpali, rupanya ada seorang Mama, jawabnya harga cina yang stel. Di Maumere, hasil komoditi seperti kopra, kakao, pala, cengkeh, dan lain-lain dibeli oleh pengepul lalu dijual kembali ke orang Cina yang akan mendistribusikannya ke Surabaya. Anggapan Cina yang stel menyoal kekuatan pemilik modal yang besar dan sekaligus langsung terlihat oleh warga karena interaksi langsung. Namun, ada satu kekuasaan besar yang ada jauh dari masyarakat sekaligus mengatur kehidupan warga, termasuk harga komoditas.
Setelah kira-kira 30 menit, kami sudah tiba di Pasar Wairkoja. Aktivitas di pasar Wairkoja sangat ramai. Terlihat dari angkutan umum yang memadati jalanan yang sempit. Oto-oto angkutan umum dan mobil pikap memenuhi badan jalan, dan seringkali mengakibatkan macet. Terdengar suara penjual obat berusaha menggaet hati pembeli. Suara itu nyaris menguasai pintu masuk pasar karena si penjual obat menggunakan pengeras suara.
Pasar ini menjadi salah satu pasar terdekat untuk beberapa kecamatan di Sikka. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan turun ke pasar membawa hasil bumi berupa kelapa, pisang, umbi-umbian, sirih-pinang serta beberapa hasil bumi lainnya.
Papalele juga bersiap menunggu di pertigaan jalan untuk membeli jualan dari tangan pertama. Papalele adalah julukan untuk pedagang tangan kedua entah laki-laki maupun perempuan yang membeli secara borongan hasil bumi dari mama-mama penjual. Di beberapa wilayah di timur Indonesia, orang juga mengenal istilah papalele yang ditujukan untuk para pedagang ikan. Namun, istilah papalele pada penerapannya ternyata ditujukan pada segala macam penjual pinggiran, seperti penjual buah, ikan, sayur, dan lain-lain.
Aktivitas barter yang saya temui di pasar Wairkoja mengingatkan saya pada cerita Ibu saya. Ibu selalu pergi ke pasar setiap Jumat sejak saya masih dalam kandungannya. Ibu berangkat subuh untuk melakukan barter atau dalam bahasa lokal disebut selung. Ibu melakukannya dari usia kandungan masih muda hingga mencapai delapan bulan. Ke pasar adalah aktivitas rutin baginya. Mendengar cerita itu, saya cukup kagum, artinya saya diboyong ketika Ibu berangkat ke pasar sambil menenteng barang-barang lainnya. Bisa dibayangkan betapa sibuknya Ibu saat itu. Sepulang dari pasar ibu membawa berbagai jenis ikan kering dengan nama yang dihafal satu per satu, tidak lupa bumbu dapur seperti garam laut. Tidak lupa pesanan wajib dari kami: roti goreng “Tanta Kedo’’. Roti goreng yang terbuat dari adonan tepung terigu kental dengan beberapa bahan dasar lainnya.
Barter rupanya telah terjalin lama antara masyarakat yang mendiami wilayah pesisir seperti pulau Pemana, Koja Doi, Selayar, dan Parumaan, orang lokal menyebutnya ata lau pulo atau ata goan dengan orang gunung atau ata ilin. Ketika aktivitas barter berlangsung, orang Pulo menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sikka sepaket dengan dialeknya. Hal ini memudahkan aktivitas transaksional tersebut. Bagi saya barter jadi sarana bertukar gizi antara orang pesisir dan orang gunung.
Menelusuri setiap sudut pasar Wairkoja seperti melihat dan mendengar kembali kamus-kamus bahasa lokal yang masih terawat di sana. Cukup asing di telinga saya saat mendengar nama sayur bopo, ko’o (sayur paku), wai talo, ‘rata otek (kenikir), kligong, puhe beta (tapak kuda), poho (daun kentut) dan lain sebagainya. Ibu saya dan perempuan lainnya begitu mahir menyebut nama masing-masing sayur dalam bahasa daerah. Berbagai jenis kacang-kacangan juga dengan mudah saya temui di pasar Wairkoja.
Biasanya mama-mama menjunjung keranjang ‘lilin atau kata dari anyaman daun lontar atau daun kelapa, di dalamnya pasti berisi serba-serbi barang dagangan termasuk kacang-kacangan. Warna dan bentuk kacang-kacangan yang saya lihat di salah satu lapak sederhana seorang nenek itu sangat beragam. Saya pun bertanya nama kacang-kacangan itu dalam bahasa daerah. Sontak saja nenek itu langsung menjawabnya: Ada wewe tana, bue, biha wona lengkap dengan cara pengolahannya. Ada juga satuan-satuan dalam lokal masih terawat di pasar ini, subur ha sama dengan 40 buah, ha tali sama dengan dua buah, liwut ha sama dengan 4 buah, beser ha sama dengan 100 batang (khusus jagung), lepong ha (penyebutan untuk garam).
Kondisi pasar menjadi ruang publik yang fleksibel bagi semua orang, sebagaimana nama pasar dalam bahasa daerah; regang yang berarti temu, menjadi titik kumpul orang untuk sekadar bertemu, bercengkerama dan bercerita. Pergi dan bertransaksi di pasar tidak hanya suatu siasat agar asap dapur tetap mengepul, tetapi juga menjadi media pertemuan dan interaksi yang dilakoni kaum perempuan, bisa juga untuk refreshing ala kadarnya. Berpapasan dengan saudara atau kerabat jauh yang tidak sengaja ditemui di pasar menjadi hal yang menyenangkan bagi mama-mama yang hari-harinya berkutat dengan urusan dapur, kebun, dan hal-hal domestik lain. Ada kesenangan lain datang ke pasar dan hanya duduk di tedang atau bale-bale bersama mama-mama lainnya di pasar sambil makan sirih pinang.
Pasar Wairkoja adalah tempat saya dapat menjumpai penamaan pangan lokal yang sudah cukup asing di telinga. Saya juga menemukan kembali penyebutan takaran pangan yang dijual atau barter dalam bahasa lokal. Adanya pangan lokal dan sebutan-sebutannya dalam bahasa lokal di pasar tradisional menjadi bukti bahwa keanekaragaman hayati itu masih ada.
Terlepas pada citra kapitalis yang melekat pada pasar sebagai tempat perputaran ekonomi di mana berlaku hukum permintaan dan penawaran, sebenarnya ada ruang resistensi yang diilhami–tanpa disadari– oleh kaum perempuan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu.
Penulis: Theresia Stevanita (Peserta Workshop “Menulis Kota dengan Perspektif Gender” dalam Festival Maumerelogia 5)