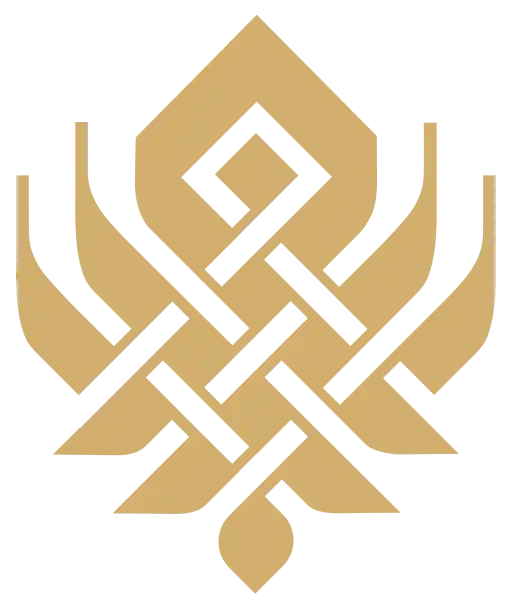Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Sikka-Krowe, wujud tertinggi dirujuk sebagai “ina nian tana wawa, ama lero wulan reta” yang secara harafiah berarti “ibu bumi tanah di bawah, bapa matahari bulan di atas.”
Ina (ibu) dalam konteks masyarakat Sikka-Krowe selalu diasosiasikan dengan bumi, tanah, kebun, panen, dan makanan. Kerja-kerja merawat tanah, bumi, tanaman, dan sumber makanan, dengan demikian, merupakan kerja-kerja merawat Ina (ibu).
Lewat akar-akar yang bergelantungan dan berserakkan di panggung, Abu dan Puri mengajak para penonton merefleksikan kembali relasi kita dan tanah, anak dan ibu.
Ramut Baler merupakan pertunjukan kolaborasi Abu Grey dan Puri Senja. Abu dan Puri adalah dua seniman tari yang melakukan residensi di Maumere. Abu tumbuh dan besar di Papua, sementara Puri di Jawa Timur.
Selama residensi, keduanya mengunjungi berbagai tempat di Maumere seperti Tanjung Kajuwulu, kampung Wuring, hutan bakau di desa Reroroja, dan kampung Nangahale.
Abu dan Puri tidak sekedar berkunjung ke tempat-tempat tersebut layaknya wisatawan. Mereka menyusuri kisah-kisah di sekeliling tempat-tempat tersebut, bertemu dan melihat dari dekat bagaimana masyarakat di tempat-tempat tersebut tinggal, serta bagaimana lingkungan dan situasi masyarakat tersebut membentuk pengalaman ketubuhan mereka.
Pertunjukan Ramut Baler dibuka dengan panggung remang, seolah meniru rahim tanah. Cahaya kuning kemerahan memancar, menciptakan suasana hutan imajiner, di mana ranting-ranting digantung terbalik, seperti akar yang tidak tahu arah.
Cahaya putih kekuningan menyoroti tubuh Puri yang dalam posisi terbalik, seolah berdiri di atas kepalanya. Kaki Puri menjulang ke atas, digerakkan menyerupai bentuk akar yang menetas dari dalam tanah.
Sementara itu, Abu sibuk mengikatkan tali-temali dari satu akar ke akar lainnya yang berserakkan di atas panggung.
Keduanya, tampak tidak peduli dengan kehadiran masing-masing.
Kemudian, dalam keheningan yang dililit tali dan dikerumuni akar-akar yang menggantung, Puri dan Abu berinteraksi dengan saling merespon gerak tubuh masing-masing. Waktu terasa berpacu mengikuti gerakan mereka dari satu sisi ke sisi lain panggung.
Abu dan Puri—seperti dua jiwa yang mencari jalan keluar dari tubuhnya sendiri—menyusuri panggung dengan gerak lirih, menyeret ranting, menyentuh tanah, berbicara dengan diam.
Abu dan Puri menampilkan tubuh mereka bukan hanya alat ungkap, tapi juga medium dengar. Kita menyaksikan bagaimana tubuh bisa mendengar kegelisahan rumah yang tak lagi nyaman, agama yang tak lagi hangat, dan masyarakat yang mulai tak saling kenal.
Ramut Baler adalah nyanyian tubuh yang menelusuri retakan-retakan sunyi: Retak di antara rumah dan agama, antara adat dan strategi hidup, antara keinginan untuk pulang dan keperluan untuk pergi.
Gerak-gerak terputus, tarikan napas yang terdengar lirih dari speaker panggung, dan sesekali suara ranting patah—semua menjadi bahasa yang tak memerlukan terjemahan.
Dalam setiap langkah yang tertahan, dalam setiap pelukan yang retak, kita diajak bertanya ulang: Benarkah akar selalu tumbuh ke bawah?
Dalam adegan selanjutnya, lampu merah menyala penuh, latar menjadi kosong, dan Abu serta Puri saling mendekat. Mereka berpelukan, bukan dalam kasih, tapi dalam luka.
Pelukan itu bukan jawaban, melainkan pertanyaan: Jika akar kita tumbuh dari trauma, bisakah kita tetap menyebutnya tanah kelahiran? Di sekitar mereka, ranting dan akar berserakan, membentuk semacam sarang atau reruntuhan, atau keduanya sekaligus.
Kekuatan pertunjukan Ramut Baler terletak pada kesederhanaannya yang dalam. Tanpa efek yang berlebihan, tanpa narasi verbal yang menggurui, Ramut Baler berhasil menggugah dialog batin penontonnya.
Tidak ada tokoh utama, sebab semua tubuh adalah pusat. Tidak ada konflik yang diselesaikan, sebab kehidupan tidak selalu menyajikan resolusi.
Abu dan Puri, dalam keheningan gerak dan keramaian akar dan tali, membangun dunia kecil yang reflektif: Tubuh mereka menjadi akar yang tumbuh ke segala arah—kadang ke langit, kadang ke luka masa lalu, kadang ke kemungkinan yang belum punya nama.
Mereka tidak menawarkan solusi, tetapi membuka ruang untuk kita menggali diri: Apa yang menjadi akar bagi keberadaan kita?
Di akhir pertunjukan, lampu mulai redup. Abu dan Puri perlahan mundur ke sisi panggung, membiarkan ranting-ranting yang mereka kumpulkan di tengah panggung menjadi pusat perhatian. Tidak ada tepuk tangan meriah, hanya keheningan penuh arti.
Seperti tanah yang diam tapi hidup, pertunjukan ini meninggalkan getar dalam dada—getar yang tidak langsung menguap begitu pertunjukan selesai.
Ramut Baler adalah pertunjukan yang membumi dan menggugah. Ia menolak untuk menjadi hiburan semata; ia memilih menjadi tanya yang menetap. Ia tidak hanya bicara tentang akar sebagai simbol tradisi atau budaya, tapi juga sebagai metafora tubuh yang memilih arah tumbuhnya sendiri.
Melalui tubuh-tubuh yang jujur, melalui gerak yang nyaris bisu, Abu dan Puri menghadirkan tafsir baru tentang menjadi manusia di tengah dunia yang terus berubah.
Mereka tidak berdiri di panggung untuk menunjukkan sesuatu, tapi untuk mengajak kita semua ikut mencari di antara akar yang berserakan dan bergelantungan.
Di mana sebenarnya akar kita? Dan jika akar itu terbalik, mungkinkah kita sedang tumbuh dengan berpijak pada langit? Mungkinkah kita sedang meninggalkan Ina (ibu) kita?
Penulis: Dimas Radjalewa