Saya datang malam itu tanpa ekspektasi. Hanya niat sederhana: Menikmati sebuah pertunjukan tari. Tapi di balik gerak tubuh yang berirama, saya justru disambut refleksi tentang manusia, tentang bagaimana kita terikat, berjuang, dan mencintai.
Pertunjukan “Hands That Hold” yang ditampilkan oleh Mega Buana dan Tyoba bukan hanya sajian estetika gerak. Ia adalah narasi eksistensial yang mengaduk ruang psikis dan filosofis penontonnya.
Dua tubuh yang terikat tali membuka pertunjukan: Secara kasat mata, tampak seperti batasan. Namun, di balik itu, jalinan tali itu adalah metafora kehidupan. Sebuah perumpamaan yang memperlihatkan bahwa kita lahir tidak dalam ruang hampa, tapi dalam jaringan kompleks: trauma masa lalu, pola asuh, keyakinan turun-temurun, cinta yang tertinggal. Benang-benang yang membentuk siapa kita, tapi seringkali tidak kita sadari mengendalikan bagaimana kita hadir dalam relasi.
Dalam studi psikologi, ini disebut sebagai attachment pattern, pola keterikatan yang membentuk bagaimana kita mencintai dan menyambut cinta.
Tarian Mega dan Tyoba menampilkan itu dengan halus dan nyaris tanpa kata. Dalam dunia yang terlalu bising, mereka justru memilih keheningan tubuh sebagai bahasa.
Keheningan itu menjadi bunyi paling ramai di kepala saya dan mungkin saja dalam benak semua audiens yang hadir di sana. Mencari-cari makna, menebak-nebak arti dari gerak yang patah, merunduk, saling menjangkau, lalu kembali terlepas. Seperti banyak relasi di kota-kota besar di mana manusia saling bersentuhan tapi tak pernah benar-benar ‘bersentuh’.
Di dalam konteks kota Maumere, saya diajak melihat relasi antara kepala dan tubuh, antara warga dan ruang-ruang kota, antara generasi satu dengan yang lainnya, membentuk cerita, warisan tetapi juga luka di sekujur peta kota ini. Gerakan Mega dan Tyoba yang berguling melepaskan tali membentangkan sebuah scenery di imaji saya tentang kita yang berusaha melepaskan diri dari apa yang disebut “ketinggalan” oleh tekanan modernitas dengan standarnya sendiri akan kemajuan global.
Tapi usaha kota ini menanggapi perubahan itu juga menghadirkan konsekuensi yang serius: Ketercerabutan dari akar kultur atau identitasnya sendiri. Dalam dinamika itu, Maumere berada pada fase “kebingungan” antara maju dan menyetarakan atau kembali dan menjaga aset-aset budaya yang terungkap melalui sistem pengetahuan dan aneka bentuk warisan leluhur lainnya.
Situasi ini memperoleh penggambaran visual yang apik dalam koreografi Mega dan Tyoba di tengah pertunjukan: berlarian, mencoba merangkul, kemudian terlepas dan melepaskan, menggenggam dan di waktu yang sama memberi jarak. Beberapa kali ada jeda singkat di antara adegan. Saya pikir mereka memberi ruang bagi diri untuk mengambil nafas, demikian kota ini juga memerlukan jeda yang sama: berefleksi.
Kita hidup dalam kultur urban yang, menurut sosiolog Georg Simmel, memisahkan manusia dari pengalaman tubuhnya sendiri. Interaksi menjadi transaksional. Waktu menjadi mata uang. Emosi dikompresi dalam emoji. Tapi tubuh tetap menyimpan jejak-memori, rasa takut, hasrat untuk disayangi.
Tarian ini menjadi semacam upaya perlawanan terhadap keterputusan itu. Ia mengajak kita kembali mendengar tubuh, memahami bahwa cinta tak melulu tentang hasrat besar, melainkan keberanian kecil untuk tetap tinggal saat dunia menyuruh pergi. Saya pikir, keberanian yang sama juga telah, sedang dan semoga terus dimiliki oleh Maumere, kita, untuk mempertahankan apa-apa yang menjadi sejarah, kebijaksanaan juga rasa cinta yang mendarah dalam nadi kota ini.
Menariknya, berpapasan dengan situasi serba terikat itu, Mega dan Tyoba, bagi saya, tidak saling menyelamatkan. Mereka saling menemani. Dan itu jauh lebih radikal. Dalam filsafat Emmanuel Levinas, keberadaan kita yang paling etis adalah ketika kita hadir sebagai “wajah” bagi yang lain: Bukan untuk mengubah, tapi untuk mengakui keberadaannya. Di sini, cinta bukanlah kepemilikan. Ia adalah pengakuan.
Pertunjukan ini juga memantik percakapan tentang bagaimana kota membentuk cara kita mencintai. Arsitektur kota yang vertikal, relasi sosial yang terputus, hingga budaya performatif media sosial menciptakan cinta yang cepat dan dangkal.
Tapi “Hands That Hold” menyuguhkan narasi tandingan: bahwa cinta bisa menjadi ruang kontemplasi. Ia tidak butuh panggung megah. Ia hidup dalam pelukan sunyi yang mengakui luka tanpa menuntut untuk disembuhkan. Serupa itu, mengakui bahwa kota kita memiliki banyak luka-luka termasuk akibat kolonialisasi adalah langkah kita membuka jalan rekonsiliasi kolektif atas peristiwa-peristiwa kota yang mempengaruhi keterlepasan kita satu sama lain dari akar kita sendiri.
Sampai pada Adegan terakhir-pelukan- dari lanskap kota, saya kembali pada diri sendiri. Menurutku, itu bukanlah klimaks romantik tapi sebuah afirmasi eksistensial: Bahwa dalam dunia yang sering tidak ramah, tetap ada tangan yang bersedia tinggal. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi, sebagai teman.
Bagi saya, pertunjukan ini adalah bentuk perlawanan terhadap relasi individualistik. Ia mengajak kita membayangkan kembali cara manusia saling hadir. Bahwa mencintai bukanlah proyek penyelamatan, tapi keterampilan mendengar, melihat, dan menerima. Seperti kata Bell Hooks, “Love is an action, never simply a feeling.”
“Hands That Hold” bukan hanya karya tari. Ia adalah meditasi kolektif tentang bagaimana menjadi manusia, menjadi masyarakat, menjadi kota, atau apa pun nama keberadaan kita. Dan mungkin, di tengah simpul-simpul kehidupan, yang kita butuhkan bukan jawaban. Tapi seseorang yang bersedia menari bersama. Seseorang yang bersedia terus berjuang meski gemetaran.
Akhirnya, saya berterimakasih kepada Mega dan Tyoba untuk karya seninya yang manis, relevan dan reflektif.













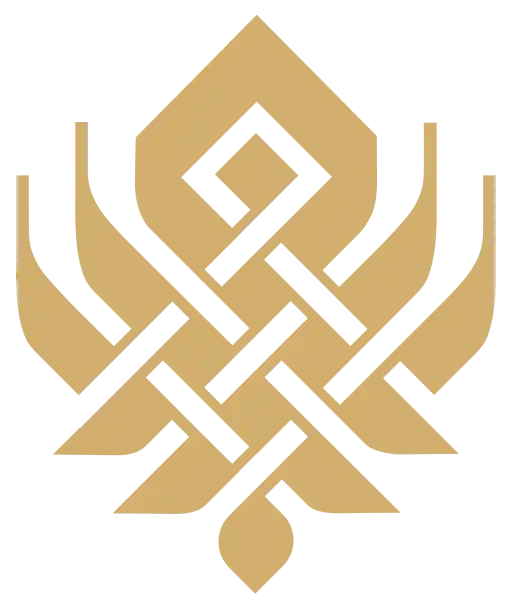


Than you very much.,ini tidak hanya permainan kata, atau seni bahasa. Tetapi lebih pada refleksi yg syarat makna, tentang Aku dan Dunia yg belum selesai💯🙏❤️
Terimakasih untuk tulisan ini.. Saya tidak sempat menonton langsung pertunjukan tersebut, namun melalui tulisan ini saya bisa membayangkan & merefleksikan pertunjukan tersebut 🤍✨