Sisi gelap kolonialitas yang hadir bersamaan dengan modernitas dalam berbagai bentuk dan agensinya menjadi topik hangat yang didiskusikan dalam kuliah umum di Aula Maximum lantai 3, Kampus 2 IFTK Ledalero bertajuk “Teori Dekolonial: Pengantar Merawat Masa Depan Selatan”, Jumat, 16 Mei 2025.
Acara ini menghadirkan Ugoran Prasad – seorang fiksionis, dramaturg, sekaligus cendekia pertunjukan dengan latar pendidikan doktor filsafat teater – sebagai narasumber utama dan dimoderatori oleh Cosmas R. Radjalewa. Dimulai pukul 10.00 WITA, forum ini bukan sekadar ruang kontemplatif, tetapi terutama ruang kritis-politis yang membongkar ulang sejajarah dan rentetan warisan kolonial dalam masyarakat kontemporer Indonesia, khususnya di wilayah timur.
Dalam pengantarnya, moderator mengajak peserta untuk merespons satu pertanyaan reflektif, “Apa yang kamu rasakan atau pikirkan saat membaca kata dekolonial?”
Pertanyaan itu menjadi pintu masuk menuju diskusi mendalam tentang bagaimana kolonialitas bukan hanya tinggal dalam sejarah, tetapi hidup dalam paradigma atau cara berpikir, metode berbahasa, dan berbagai kedok kekuasaan.
Dalam penjelasannya, Ugoran Prasad menerangkan bahwa dalam banyak konteks kota yang berkembang, termasuk di wilayah timur Indonesia, masyarakat seringkali menerima modernitas tanpa sikap kritis. Proses modernisasi bahkan dianggap sebagai hal yang given atau terberi, sesuatu fase yang seakan-akan menjadi niscaya dan harus dilalui oleh negara atau bangsa tanpa ada upaya melacak latar epistemiknya.
Dalam situasi yang demikian, ‘kemajuan’ pun kerap dimaknai semata-mata sebagai pertumbuhan ekonomi, pendidikan formal, dan teknologi, semuanya dengan ukuran Barat yang developmentalis dan liberalis. Karenanya, tradisi, bahasa ibu, dan pengetahuan lokal sering kali hanya disinonimkan dengan masa lalu yang dianggap harus ditinggalkan.
Lebih jauh Ugo mengangkat pemikiran Aníbal Quijano, yang memperkenalkan konsep coloniality of power atau kolonialitas kekuasaan. Bahwa kolonialitas selalu mungkin beroperasi dalam pemahaman kita akan pengetahuan, ras, gender dan kebudayaan. Dengan demikian, modernitas merupakan kelanjutan dari kolonialisme.
Adapun acara yang diinisiasi oleh Komunitas Kahe dengan tema umum Kultur, Kota, Kita ini, dihadiri oleh berbagai kalangan, di antaranya: civitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Maumere, Univeritas Nusa Nipa, IFTK Ledalero, birokrat, warga sipil, para seniman lokal maupun residen dari Papua, Madura, Surabaya, Jogja, Solo, Jakarta, serta beberapa partisipan lainnya.
Melihat banyak banyak partisipannya adalah para seniman, Ugo pun mengerahkan diskusi tertuju pada bagaimana seni, teater, dan praktik kebudayaan bisa menjadi alat perlawanan terhadap kolonialitas, atau sebaliknya, bisa terseret menjadi alat propaganda neoliberalisme.
“Seni yang lepas dari akar warga, dari pengalaman sehari-hari, rawan menjadi komoditas semata. Namun ketika seni berpihak, ia bisa jadi opsi dekolonial atau menjadi alat pembebasan,” ujar Ugoran.
Sebagai contoh konkret, komunitas KAHE di Maumere bisa jadi salah satu jangkar dekolonialitas kultural di wilayah timur. Melalui festival warga, residensi seniman, dan ruang dialog lintas identitas, KAHE dapat membangun jembatan yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan praktik seni kontemporer.
“Pertemuan warga dan seniman dalam ruang-ruang seperti ini bisa melampaui ketegangan-ketegangan imperial yang diwariskan sejarah. Karenanya festival warga bisa dilihat bukan sekadar pertunjukan, tapi sebagai pembukaan ruang negosiasi dan pertukaran makna yang hidup,” tambah Ugo.
Dengan demikian acara Lectio Brevis atau kuliah umum ini bukan sekadar peristiwa akademik, melainkan bagian dari inisiatif gerak bersama untuk membangun kesadaran, merebut kembali narasi dan masa depan.













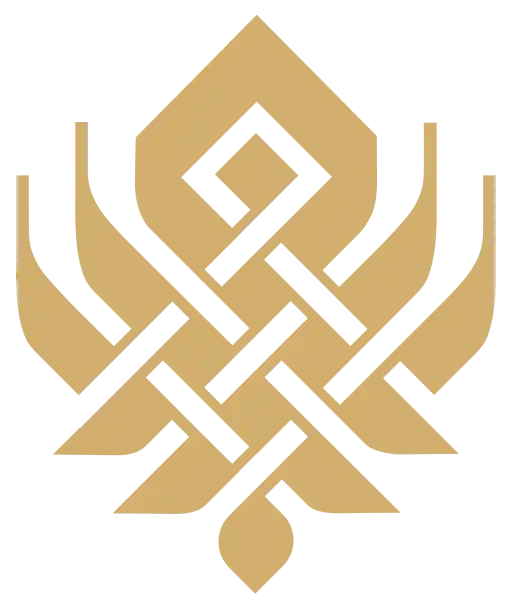


Keren banget pembahasannya. Saya sangat setuju.
Pemikiran kolonialisme masih melekat terhadap masyrakat Indonesia sekarang, seperti menggangap budaya barat jauh lebih modern dibandingkan dengan budaya negara sendiri, produk luar negeri is better than local product dan masih banyak lagi.
Penindasan terhadap pengetahuan lokal atau tradisional oleh pengetahuan dominan (misalnya, ilmu Barat dianggap satu-satunya yang sah, sedangkan pengetahuan adat dianggap tidak ilmiah). Padahal, hal-hal tersebut sebenarnya adalah warisan budaya dan identitas penting yang justru bisa menjadi sumber kekayaan dan kebijaksanaan bangsa.